KH. Abdul hamid Lahir
pada tahun 1333 H, di Desa Sumber Girang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah.Wafat 25
Desember 1985. Pendidikan: Pesantren Talangsari, Jember; Pesantren Kasingan,
Rembang, Jateng; Pesantren Termas, Pacitan, Jatim. Pengabdian: pengasuh
Pesantren Salafiyah, Pasuruan
Kesabarannya memang
diakui tidak hanya oleh para santri, tapi juga oleh keluarga dan masyarakat
serta umat islam yang pernah mengenalnya. Sangat jarang ia marah, baik kepada
santri maupun kepada anak dan istrinya. Kesabaran Kiai Hamid di hari tua,
khususnya setelah menikah, sebenarnya kontras dengan sifat kerasnya di masa
muda.
“Kiai Hamid dulu
sangat keras,” kata Kiai Hasan Abdillah. Kiai Hamid lahir di Sumber Girang,
sebuah desa di Lasem, Rembang, Jawa Tengah, pada tahun 1333 H. Ia adalah anak
ketiga dari tujuh belas bersaudara, lima di antaranya saudara seibu. Kini, di
antara ke 12 saudara kandungnya, tinggal dua orang yang masih hidup, yaitu Kiai
Abdur Rahim, Lasem, dan Halimah. Sedang dari lima saudara seibunya, tiga orang
masih hidup, yaitu Marhamah, Maimanah dan Nashriyah, ketiganya di
Pasuruan. Hamid dibesarkan di tengah keluarga santri. Ayahnya, Kiai umar,
adaiah seorang ulama di Lasem, dan ibunya adalah anak Kiai Shiddiq, juga ulama
di Lasem dan meninggal di Jember, Jawa Timur.
Masa Kecil
Kiai Shiddiq adalah
ayah KH. Machfudz Shiddiq, tokoh NU, dan KH. Ahmad Shiddiq, mantan Ro’is Am NU.
Keluarga Hamid memang memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan dunia
pesantren. Sebagaimana saudara-saudaranya yang lain, Hamid sejak kecil
dipersiapkan untuk menjadi kiai. Anak keempat itu mula-mula belajar membaca
al-Quran dari ayahnya. Pada umur sembilan tahun, ayahnya mulai mengajarinya
ilmu fiqh dasar.
Tiga tahun kemudian,
cucu kesayangan itu mulai pisah dari orangtua, untuk menimba ilmu di pesantren
kakeknya, KH. Shiddiq, di Talangsari, Jember, Jawa Timur. Konon, demikian
penuturan Kiai Hasan Abdillah, Kiai Hamid sangat disayang baik oleh ayah maupun
kakeknya. Semasih kecil, sudah tampak tanda-tanda bahwa ia bakal menjadi wali
dan ulama besar.
“Pada usia enam
tahun, ia sudah bertemu dengan Rasulullah,” katanya. Dalam kepercayaan yang
berkembang di kalangan warga NU, khususnya kaum sufi, Rasulullah walau telah
wafat sekali waktu menemui orang-orang tertentu, khususnya para wali.
Bukan
dalam mimpi saja, tapi secara nyata.
Pertemuan dengan
Rasul menjadi semacam legitimasi bagi kewalian seseorang. Kiai Hamid mulai
mengaji fiqh dari ayahnya dan para ulama di Lasem. Pada usia 12 tahun, ia mulai
berkelana. Mula-mula ia belajar di pesantren kakeknya, KH. Shiddiq, di
Talangsari, Jember.
Tiga tahun kemudian ia diajak kakeknya untuk pergi haji
yang pertama kali bersama keluarga, paman-paman serta bibi-bibinya. Tak lama
kemudian dia pindah ke pesantren di Kasingan, Rembang. Di desa itu dan
desa-desa sekitarnya, ia belajar fiqh, hadits, tafsir dan lain lain. Pada usia
18 tahun, ia pindah lagi ke Termas, Pacitan, Jawa Timur.
Konon, seperti
dituturkan anak bungsunya yang kini menggantikannya sebagai pengasuh Pesantren
Salafiyah, H. Idris, “Pesantren itu sudah cukup maju untuk ukuran zamannya,
dengan administrasi yang cukup rapi. Pesantren yang diasuh Kiai Dimyathi itu
telah melahirkan banyak ulama terkemuka, antara lain KH Ali Ma’shum, mantan Ro’is
Am NU.” Menurut Idris, inilah pesantren yang telah banyak berperan dalam
pembentukan bobot keilmuan Hamid.
Di sini ia juga belajar berbagai ilmu
keislaman. Sepulang dari pesantren itu, ia tinggal di Pasuruan, bersama
orangtuanya. Di sini pun semangat keilmuannya tak pernah Padam. Dengan tekun,
setiap hari ia mengikuti pengajian Habib Ja’far, ulama besar di Pasuruan saat
itu, tentang ilmu tasawwuf.
Menjadi Blantik
Hamid menikah pada
usia 22 tahun dengan sepupunya sendiri, Nyai H. Nafisah, putri KH Ahmad Qusyairi.
Pasangan ini dikarunia enam anak, satu di antaranya putri. Kini tinggal tiga
orang yang masih hidup, yaitu H. Nu’man, H. Nasikh dan H. Idris.
Hamid menjalani
masa-masa awal kehidupan berkeluarganya tidak dengan mudah. Selama beberapa
tahun ia harus hidup bersama mertuanya di rumah yang jauh dari mewah. Untuk
menghidupi keluarganya, tiap hari ia mengayuh sepeda sejauh 30 km pulang pergi,
sebagai blantik (broker) sepeda. Sebab, kata ldris, pasar sepeda waktu itu ada
di desa Porong, Pasuruan, 30 km ke arah barat Kotamadya Pasuruan.
Kesabarannya bersama
juga diuji. Hasan Abdillah menuturkan, Nafisah yang dikawinkan orangtuanya
selama dua tahun tidak patut (tidak mau akur). Namun ia menghadapinya dengan
tabah. Kematian bayi pertama, Anas, telah mengantar mendung di rumah keluarga
muda itu.
Terutama bagi sang
istri Nafisah yang begitu gundah, sehingga Hamid merasa perlu mengajak istrinya
itu ke Bali, sebagai pelipur lara. Sekali lagi Nafisah dirundung kesusahan yang
amat sangat setelah bayinya yang kedua, Zainab, meninggal dunia pula, padahal
umurnya baru beberapa bulan. Lagi-lagi kiai yang bijak itu membawanya
bertamasya ke tempat lain. KH. Hasan Abdillah, adik istri Kiai Hamid,
menuturkan, seperti layaknya keluarga, Kiai Hamid pernah tidak disapa oleh istrinya
selama empat tahun.
Tapi, tak pernah
sekalipun terdengar keluhan darinya. Bahkan sedemikian rupa ia dapat
menutupinya sehingga tak ada orang lain yang mengetanuinya. “Uwong tuo kapan
ndak digudo karo anak Utowo keluarga, ndak endang munggah derajate (Orangtua
kalau tidak pernah mendapat cobaan dari anak atau keluarga, ia tidak lekas naik
derajatnya)”, katanya suatu kali mengenai ulah seorang anaknya yang agak
merepotkan.
Kesabaran beliau juga
diterapkan dalam mendidik anak-anaknya. Menut Idris, tidak pernah mendapat
marah, apalagi pukulan dari ayahnya. Menurut ldris, ayahnya lebih banyak
memberikan pendidikan lewat keteladanan. Nasihat sangat jarang diberikan. Akan
tetapi, untuk hal-hal yang sangat prinsip, shalat misalnya, Hamid sangat tegas.
Merupakan keharusan
bagi anak-anaknya untuk bangun pada saat fajar menyingsing, guna menunaikan
shalat subuh, meski seringkali orang lain yang disuruh membangunkan mereka,
Hamid juga memberi pengajaran membaca al-Quran dan fiqih pada anak-anaknya di
masa kecil. Namun, begitu mereka menginjak remaja, Hamid lebih suka menyerahkan
anak-anaknya ke pesantren lain.
Bukan hanya kepada
anak-anak, tapi juga istrinya, Hamid memberi pengajaran. Waktunya tidak pasti.
Kitab yang diajarkan pun tidak pasti. Bahkan, ia mengajar tidak secara
berurutan dari bab satu ke bab berikutnya. Pendeknya, ia seperti asal comot
kitab, lalu dibuka, dan diajarkan pada istrinya. Dan lebih banyak, kata Idris,
yang diajarkan adalah kitab-kitab mengenai akhlak, seperti Bidayah al-Hidayah
karya Imam Ghazali, “Tampaknya yang lebih ditekankan adalah amalan, dan bukan
ilmunya itu sendiri,” jelasnya.
Amalan dari kitab itu
pula yang ditekankan Kiai Hamid di Pesantren salafiyah. Kalau
pesantren-pesantren tertentu dikenal dengan spesialisasinya dalam bidang-bidang
ilmu tertentu – misainya alat (gramatika bahasa Arab) atau fiqh, maka salafiyah
menonjol sebagai suatu lembaga untuk mencetak perilaku seorang santri yang
baik.
Di sini, Kiai Hamid
mewajibkan para santrinya shalat berjamaah lima waktu. Sementara jadwal
kegiatan pesantren lebih banyak diisi dengan kegiatan wirid yang hampir
memenuhi jam aktif. Semuanya harus diikuti oleh seluruh santri. Kiai Hamid
sendiri, tidak banyak mengajar, kecuali kepada santri-santri tertentu yang
dipilihnya sendiri. Selain itu, khususnya di masa-masa akhir kehidupannya, ia
hanya mengajar seminggu sekali, untuk umum.
Mushalla pesantren
dan pelatarannya setiap Ahad selalu penuh oleh pengunjung untuk mengikuti
pengajian selepas salat subuh ini. Mereka tidak hanya datang dari Pasuruan,
tapi juga kota-kota Malang, Jember, bahkan Banyuwangi, termasuk Walikota Malang
waktu itu. Yang diajarkan adalah kitab Bidayah al-Hidayah karya al-Ghazali.
Konon, dalam setiap pengajian, ia hanya membaca beberapa baris dari kitab itu.
Selebihnya adalah
cerita-cerita tentang ulama-ulama masa lalu sebagai teladan. Tak jarang, air
matanya mengucur deras ketika bercerita. Disuguhi Kulit Roti Kiai Hamid memang
sosok ulama sufi, pengagum imam Al-Ghazali dengan kitab-kitabnya lhya ‘Ulum
ad-Din dan Bidayah al-Hidayah. Tapi, corak kesufian Kiai Hamid bukanlah yang
menolak dunia sama sekali. Ia, konon, memang selalu menolak diberi mobil
Mercedez, tapi ia mau menumpanginya. Bangunan rumah dan perabotan-perabotannya
cukup baik, meski tidak terkesan mewah.
Ia suka berpakaian
dan bersorban yang serba putih. Cara berpakaian maupun penampilannya selalu
terlihat rapi, tidak kedodoran. Pilihan pakaian yang dipakai juga tidak bisa
dibilang berkualitas rendah. “Berpakaianlah yang rapi dan baik. Biar saja kamu
di sangka orang kaya. Siapa tahu anggapan itu merupakan doa bagimu,” katanya
suatu kali kepada seorang santrinya. Namun, Kiai Hamid bukanlah orang yang suka
mengumbar nafsu. Justru, kata idris, ia selalu berusaha melawan nafsu.
Hasan Abdillah
bercerita, suatu kali Hamid berniat untuk mengekang nafsunya dengan tidak makan
nasi (tirakat). Tetapi, istrinya tidak tahu itu. Kepadanya lalu disuguhkan
roti. Untuk menyenangkannya, Hamid memakan roti itu, tapi tidak semuanya,
melainkan kulitnya saja. “O, rupanya dia suka kulit roti,” pikir istrinya.
Esoknya ia membeli roti dalam jumlah yang cukup besar, lalu menyuguhkan kepada
suaminya kulitnya saja. Kiai Hamid tertawa. “Aku bukan penggemar kulit roti.
Kalau aku memakannya kemarin, itu karena aku bertirakat,” ujarnya.
Konon, berkali-kali
Kiai Hamid ditawari mobil Mercedez oleh H. Abdul Hamid, orang kaya di Malang.
Tapi, ia selalu menolaknya dengan halus. Dan untuk tidak membuatnya kecewa,
Hamid mengatakan, ia akan menghubunginya sewaktu-waktu membutuhkan mobil itu.
Kiai Hamid memang selalu berusaha untuk tidak mengecewakan orang lain, suatu
sikap yang terbentuk dari ajaran idkhalus surur (menyenangkan orang lain)
seperti dianjurkan Nabi. Misalnya, jika bertamu dan sedang berpuasa
sunnah, ia selalu dapat menyembunyikannya kepada tuan rumah, sehingga ia tidak
merasa kecewa. Selain itu, ia selalu mendatangi undangan, di manapun dan oleh
siapapun.
Selain terbentuk oleh
ajaran idkhalus surur, sikap sosial Kiai Hamid terbentuk oleh suatu ajaran
(yang dipahami secara sederhana) mengenai kepedulian sosial islam terhadap kaum
dlu’afa yang diwujudkan dalam bentuk pemberian sedekah. Memang karikaturis –
meminjam istilah Abdurrahman Wahid tentang sifatnya.
Tapi, Kiai Hamid
memang bukan seorang ahli ekonomi yang berpikir secara lebih makro. Walau begitu,
kita dapat memperkirakan, sikap sosial Kiai Hamid bukan hanya sekadar refleksi
dari motivasi keagamaan yang “egoistis”, dalam arti hanya untuk mendapat
pahala, dan kemudian merasa lepas dari kewajiban. Kita mungkin dapat melihat,
betapa ajaran sosial islam itu sudah membentuk tanggung jawab sosial dalam
dirinya meski tidak tuntas.
Ajaran Islam,
tanggung jawab sosial mula-mula harus diterapkan kepada keluarga terdekat,
kemudian tetangga paling dekat dan seterusnya. Urut-urutan prioritas demikian
tampak pada Kiai Hamid. Kepada tetangga terdekat yang tidak mampu, konon ia
juga memberikan bantuannya secara rutin, terutama bila mereka sedang mempunyai
hajat, apakah itu untuk mengawinkan atau mengkhitan anaknya.
H. Misykat yang
mengabdi padanya hingga ia meninggal, bercerita bahwa bila ada tetangga yang
sedang punya hajat, Kiai Hamid memberi uang RP. 10.000 plus 10 kg. beras. Islam
mengajarkan, hari raya merupakan hari di mana umat Islam dianjurkan bergembira
sebagai rasa syukur setelah menunaikan lbadah puasa sebulan penuh. Menjelang
hari raya, sebagai layaknya seorang ulama, Kiai Hamid tidak menerima hadiah dan
zakat fitri.








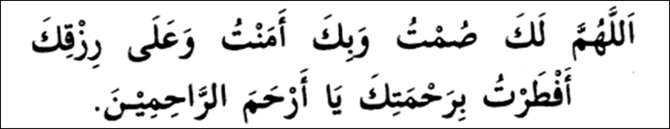
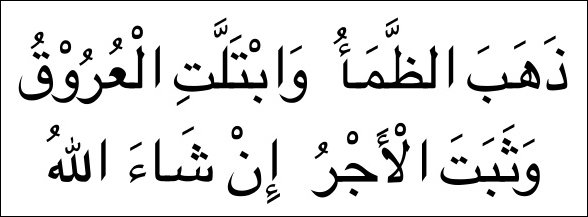



 Ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha tiba, seluruh umat Islam yang
tidak ada uzur dianjurkan untuk keluar rumah, tak terkecuali perempuan
haid. Perempuan yang sedang menstruasi memang tak dilarang untuk shalat
tapi ia dianjurkan turut mengambil keberkahan momen tersebut dan
merayakan kebaikan bersama kaum muslimin lainnya.
Ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha tiba, seluruh umat Islam yang
tidak ada uzur dianjurkan untuk keluar rumah, tak terkecuali perempuan
haid. Perempuan yang sedang menstruasi memang tak dilarang untuk shalat
tapi ia dianjurkan turut mengambil keberkahan momen tersebut dan
merayakan kebaikan bersama kaum muslimin lainnya.




